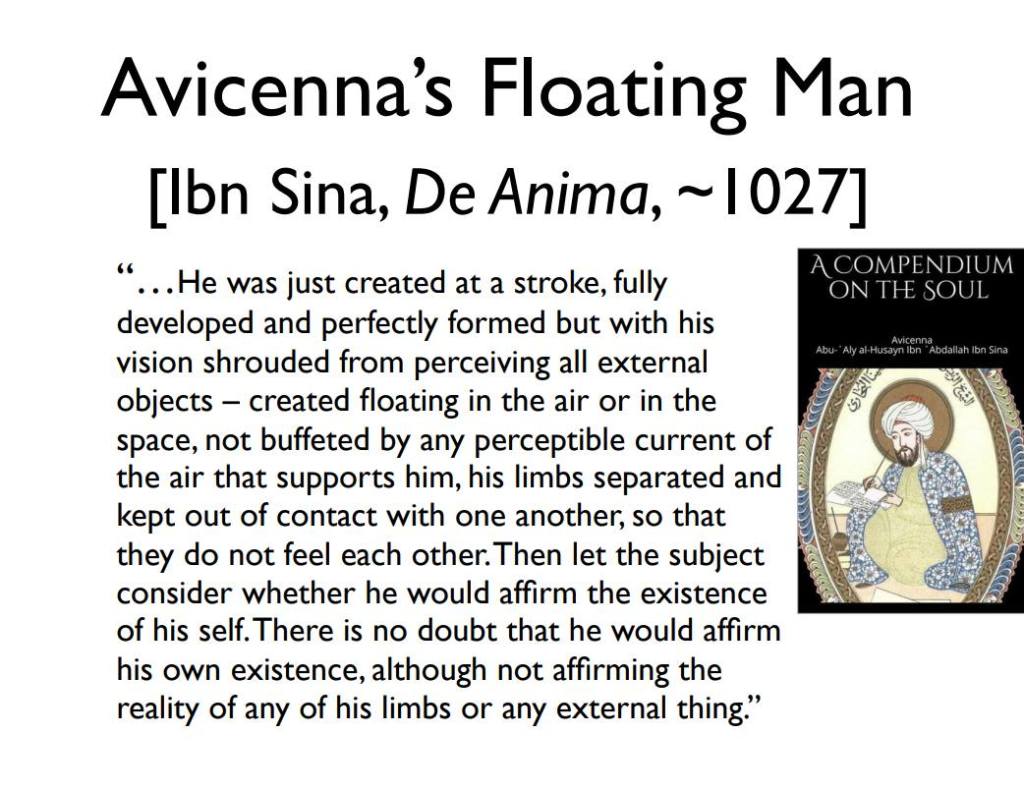“…Surely in this is a sign for those who reflect.” – Q.S. An-Naḥl (The Bee) [16]:69
Bentuk segi enam (hexagon) sarang lebah madu barangkali merupakan salah satu contoh terbaik betapa menakjubkannya ‘kerja’ alam semesta. Pertanyaan tentu timbul, bagaimana para lebah madu dapat berkoordinasi dalam membuat bentuk yang kompleks? Mengapa segi enam? Mengapa bukan lingkaran, segitiga, atau persegi? Dari sinilah, ketakjuban dan rasa penasaran berubah menjadi penelitian.
Namun demikian, persoalan bentuk segi enam sarang lebah madu sebenarnya bukanlah barang baru. Misalnya, sekitar abad ke-36 SM Marcus Terentius Varro (116-27 SM) menyebutkan alasan bentuk segi enam sarang lebah madu adalah: 1) kecocokannya dengan kaki lebah madu yang juga berjumlah enam; 2) bukti geometris bahwa bentuk segi enam mampu menghasilkan rasio luas per keliling terbesar.[1] Terkait argumen kedua, Pappus of Alexandria (290-350) juga menulis hal senada dengan menyatakan bahwa bentuk segi enam lebih baik daripada persegi atau segitiga dalam hal rasio kapasitas menyimpan madu terhadap lilin yang digunakan untuk membuat bentuk geometri bersangkutan.[2] Hingga sekarang pun masih banyak yang menjadikan bentuk sarang lebah madu ini sebagai objek penelitian.
Di antara banyak orang yang mengamati bentuk segi enam sarang lebah madu, adalah hal yang menarik bahwa dua nama besar, Abū Ḥāmid Al-Ghazālī (1058-1111) dan Charles Robert Darwin (1809-1882), termasuk didalamnya. Imam Al-Ghazālī, sebagaimana yang kita tahu, adalah seorang ulama besar di zamannya yang telah menulis berbagai macam kitab yang masih dikaji hingga saat ini – terutama Iḥyā′ ‘Ulūm al-Dīn. Darwin, sebagaimana yang kita tahu juga, merupakan seorang saintis yang terkenal karena kontribusinya dalam teori evolusi.
Namun, yang membuat dua nama itu menarik untuk dibahas bukan hanya karena ketenarannya. Bukan tujuan tulisan ini juga untuk ,enitikberatkan siapa lebih dahulu dari siapa. Sebaliknya, yang menarik untuk dibahas adalah bagaimana keduanya mengamati fenomena alam yang sama (bentuk segi enam sarang lebah madu) namun sampai pada kesimpulan yang sama sekali berbeda. Tulisan ini akan mencoba menjelaskan bagaimana berbedanya pandangan kedua sosok tersebut dan pelajaran apa yang bisa kita ambil darinya. Hal ini menarik untuk dibahas karena di tengah-tengah klaim bahwa pengamatan alam (re: sains) itu netral, kasus ini menunjukkan bahwa perbedaan filosofis sang pengamat mampu membuat kesimpulan akhirnya berbeda juga.
Oleh karena itu, pada bagian berikutnya kita akan menyelami bagaimana Al-Ghazālī dan Darwin mengamati sarang lebah madu dan apa kesimpulan yang dicapai masing-masing.
Al-Ghazālī, Sarang Lebah Madu, dan Sang Maha Pemberi Rahmat
Sekitar abad ke-12, di masa setelah Imam Al-Ghazālī menyelesaikan magnum opusnya Iḥyā′ ‘Ulūm al-Dīn dan juga ketika beliau berada di masa puncak intelektual dan spiritualnya, beliau menyelesaikan kitab berjudul Jawāhir Al-Qur’ān (The Jewels of the Qur’ān)[3] yang berisikan pemahamannya terhadap kitab suci Al-Qur’an. Adalah pada bab ke-12 yang berjudul “Secrets of the Sūra of the Opening (al-Fātiḥah), and how it comprises eight of the ten valuables of the Qur’ān” kita bisa menemukan penjelasan Al-Ghazālī tentang bentuk segi enam sarang lebah madu.
Al-Ghazālī memulai tulisannya di bab tersebut dengan membahas dua ʾasmāʾul ḥusnā yang terdapat pada surat Al-Fātiḥah: Ar-Raḥmān dan Ar-Raḥīm. Kedua ʾasmāʾul ḥusnā tersebut terdapat pada ayat pertama dan ketiga surat al-Fātiḥah. Mengapa terjadi ‘pengulangan’ penyebutan kedua nama tersebut? Beliau menulis:
The words of God, “Most Gracious, Ever Merciful” (الرحمن الرحيم), the second time, indicate His attribute once again. Do you imagine that this is a repetition? There is no repetition in the Qur’ān, for repetition is defined as that which does not contain any additional benefit. The mention of mercy after the mention of “all the worlds” and before the mention of “the Master of the Day of Judgement”, has two great benefits in expounding the channels of mercy. One pays attention to creation to creation by the Lord of all the worlds – He has created every one of these according to the most perfect and best of its kind and has given it everything it needs.[4]
Kemudian beliau menjelaskan bagaimana Allah memanifestasikan rahmat-Nya kepada hewan dengan memberi contoh nyamuk, lalat, laba-laba, dan lebah madu. Tentang lebah madu, beliau menulis:
Look at the bee and the innumerable wonders of its gathering honey and [producing] bees-wax. We [should like to] make you aware of the geometry of its hive. It is built on the figure of the hexagon in order that space may not be narrow for its companies who become crowded in one place in a great number. If it should build its hive circular, there would remain, outside the circular hive, an empty space since circles are not contiguous to one another. Likewise are all other figures. As to squares, they are contiguous to one another, but the shape of the bee is inclined to roundness and so inside the hive there would remain empty corners as, in a circular house, there would remain an empty corner outside the house. Thus none of the figures other than the hexagon approaches the circular figure in contiguity, and this is known by geometrical proof. Consider, then, how God has guided the bee to the characteristic of this figure.
This is a sample from the wonders of God’s works and His kindness and mercy to His creation, for the lowest constitutes an evidence of the highest.[5]
Dengan kata lain, Al-Ghazālī mengatakan bahwa kita dapat melihat tanda-tanda kehadiran rahmat Allah dari alam sekitar (dalam kasus ini lebah madu). Bentuk segi enam yang tepat untuk sarang lebah madu (dibandingkan dengan persegi atau lingkaran) merupakan bukti kehadiran rahmat Allah tersebut. Tentunya, lebah madu membangun sarangnya atas petunjuk Allah, sebagaimana firman-Nya:
Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, “Buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia, kemudian makanlah dari segala (macam) buah-buahan lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu).” Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berpikir. (Q.S. An-Naḥl [16]:68-69)
Barangkali, inilah salah satu contoh bagaimana alam semesta dipelajari sebagai tanda (āyāt, sign) adanya Sang Pencipta. Sebagaimana Firman Allah di surat yang lain, “Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kebesaran) Kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Alquran itu adalah benar.” (Q.S. Fuṣṣilat [41]:53)
Namun untuk sekarang kita simpan dulu pembahasan lebih lanjut tentang bagaimana Islam mendudukkan pengamatan alam (yang sekarang kita sebut sains) sebagai sarana untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Sekarang, mari kita melangkah tujuh abad ke depan (abad ke-19), tepatnya ke tahun 1859 – tahun dimana Charles Darwin pertama kali menerbitkan bukunya yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life[6], atau lebih populer disebut The Origin of Species.
Darwin, Sarang Lebah Madu, dan Seleksi Alam
Penjelasan teologis tentang sarang lebah madu bukan menjadi monopoli Al-Ghazālī atau umat Islam semata. Pada abad ke-19 pun kita masih dapat menemukan jejaknya di Barat. Hal ini dapat kita temukan misalnya pada buku Dissertations on Subjects Connected with Natural Theology (1839) oleh Lord Brougham. William Kirby juga melakukan penjelasan serupa dengan mendeskripsikan lebah madu sebagai ‘heaven-instructed mathematicians’ dalam membuat sarangnya.[7]
Darwin tentunya mengetahui penjelasan ini. Hal ini dibuktikan dengan catatannya pada buku Lord Brougham tersebut. Di salah satu halamannya, ia menulis “very wonderful – it is as wonderful in the mind as certain adaptations in the body – the eye for instance, if my theory explains one it may explain other.”[8] Maka tidaklah mengherankan jika dalam The Origin of Species, Darwin mendedikasikan bahasan khusus terkait bentuk segi enam sarang lebah madu dalam bab bertajuk Instinct (bab VII).
Darwin menyadari pentingnya membahas lebah madu pada bab ini, karena penjelasan teologis yang telah dijelaskan oleh Brougham, Kirby, dan lainnya menjadi tantangan bagi penjelasan naturalistiknya. Ia menulis:
THE subject of instinct might have been worked into the previeous chapters; but I have thought that it would be more convenient to treat the subject separately, especially as so wonderful an instinct as that of the hive-bee making its cells will probably occurred to many readers, as a difficulty sufficient to overthrow my whole theory.[9]
Namun Darwin tidak mendefinisikan naluri (instinct) secara lugas di sini. Ia hanya mengatributkannya dengan kebiasaan (habit) atau keadaan alamiah (state of nature).[10] Darwin pun menolak anggapan bahwa naluri diperoleh “dari sananya” dan tidak dapat diubah. Sejalan dengan ungkapan natura non facit saltum (nature does not make a jump), ia menulis:
But it would be the most serious error to suppose that the greater number of instincts have been acquired by habit in one generation, and then transmitted by inheritance to succeeding generations. It can be clearly shown that the most wonderful instincts with which we are acquainted, namely, those of the hive-bee and of many ants, could not possibly have been thus acquired…
Under changed conditions of life, it is at least possible that slight modifications of instinct might be profitable to a species; and it can be shown that instincts do vary ever so little, then I can see no difficulty in natural selection preserving and continually accumulating variations of instinct to any extent that may be profitable. It is thus, as I believe, that all the most complex and wonderful instincts have originated.[11]
Dengan kata lain, Darwin ingin menunjukkan bahwa naluri alamiah (seperti naluri membuat sarang lebah madu yang kompleks) sejatinya lahir dari proses iteratif yang sederhana, dan segala macam habit atau state of nature bisa berubah jika dihadapkan pada kondisi seleksi alamversi Darwin. Tentunya, untuk membuktikan teorinya tersebut, Darwin harus mengambil contoh kasus sarang lebah madu. Hal ini tidak ia lewatkan, sebagaimana tulisannya:
We shall, perhaps, best understand how instincts in a state of nature have become modified by selection, by considering a few cases. I will select only three, out of the several which I shall have to discuss in my future work, – namely, the instinct which leads the cuckoo to lay her eggs in other birds’ nests; the slave-making instinct of certain ants; and the comb-making power of the hive bee: these two latter instincts have generally, and most justly, been ranked by naturalists as the most wonderful of all known instincts.[12]
Maka Darwin perlu membuktikan dua hal: 1) bagaimana bentuk sarang lebah berkembang seiring berjalannya waktu; 2) bagaimana lebah madu membangun sarangnya dengan kerangka teori naluri yang berkembang tersebut.[13]
Untuk poin pertama, Darwin mengambil tiga contoh spesies lebah: bumblebee, hivebee (lebah madu), dan Melipona domestica Mexico. Bumblebee memiliki sarang yang berbentuk cenderung setengah bola, sementara sarang lebah madu berbentuk segi enam dengan piramida belah ketupat di ujung selnya. Sementara itu, sarang Melipona domestica mengambil bentuk pertengahan, yaitu silinder untuk sel yang kecil (berguna untuk menetaskan larva) dan setengah bola untuk sel yang besar (berguna untuk menyimpan madu).[14] Dari sinilah Darwin kemudian berteori bahwa naluri lebah didapatkan dari proses seleksi alam. Dengan kata lain, naluri lebah membuat sarang berevolusi dari acak dan sederhana (sarang setengah bola bumblebee) menjadi teratur dan kompleks (sarang segi enam lebah madu).[15] Darwin menyatakan ulang teorinya di akhir paragraf, “I believe that the hive-bee has acquired, through natural selection, her inimitable architectural powers.”[16]
Untuk poin kedua (sekaligus memperkuat argumen naluri yang terakumulasi dan seleksi alam), Darwin melakukan tiga eksperimen. Pada eksperimen pertama, ditemukan bahwa para lebah madu awalnya membuat sel berbentuk setengah bola (bentuk sederhana). Ketika dua sel kubah berdekatan dan nyaris beririsan, para lebah madu terseut kemudian membangun dinding rata antara kedua sel sehingga bentuk segi enam dapat tercapai.[17] Pada eksperimen kedua, setelah Darwin memberi lebah madu lapisan lilin yang tipis. Jika para lebah madu membangun sarang seperti biasa dan mencoba membangun piramida belah ketupat di dasar sel, maka sel tersebut akan jebol. Akan tetapi, para lebah madu justru beradaptasi dengan mebuat sel yang lebih cetek dan memiliki dasar yang lebih rata.[18] Pada eksperimen ketiga, Darwin memberikan lapisan lilin merah kepada lapisan terluar sarang lebah madu untuk mengamati bagaimana proses pembentukan selnya.[19]
Berdasarkan pengamatan ketiga jenis lebah (humblebee, Melipona domestica,dan lebah madu) serta eksperimen yang menunjukkan lebah madu membuat sarangnya dari bentuk yang lebih sederhana (setengah bola/lingkaran) menuju kompleks (segi enam), Darwin kemudian menyimpulkan bahwa naluri hewani bisa dijelaskan dengan teori seleksi alam – yaitu modifikasi naluri alamiah (state of nature) yang lebih sederhana secara perlahan. Mengutip kalimatnya, “Thus, as I believe, the most wonderful of all known instincts, that of the hive-bee, can be explained by natural selection having taken advantage of numerous, successive, slight modifications of simpler instincts.”[20]
Darwin, sebagaimana Al-Ghazālī, kemudian juga menjawab mengapa pada akhirnya lebah madu memilih bentuk segi enam. Ia mengetahui dari korespondensinya dengan Tegetmeier bahwa untuk menghasilkan 1 pound lilin, lebah madu harus mengkonsumsi 12-15 pound gula.[21] Dari sini, Darwin kemudian mengaitkan hasil pengamatannya terhadap lebah madu dengan teori seleksi alam yang ia gadang-gadang. Ia menulis:
The motive power of the process of natural selection having been economy of the wax; that individual swarm which wasted least honey in the secretion of wax, having succeeded best, and having transmitted by inheritance its newly acquired economical instinct to new swarms, which in their turn will have had the best chance of succeeding in the struggle for existence.[22]
Artinya, tidak ada yang spesial (atau dalam bahasa Kirby, ‘heaven-instructed’) dari bentuk segi enam sarang lebah madu. Hal tersebut hanyalah keluaran yang paling logis dari mekanisme seleksi alam alias survival of the fittest. Dengan demikian, Darwin berhasil memberikan alternatif penjelasan naturalistik di bidang yang sebelumnya didominasi penjelasan teologis.
Antara Al-Ghazālī, Darwin, Sains, dan Ayat Kawniyyah
Lewat bukti geometris sederhana, kita dapat membuktikan bahwa segi enam adalah bentuk yang memiliki rasio luas per keliling terbesar jika dibandingkan dengan segi tiga sama sisi dan persegi.[23] Matematikawan Thomas C. Halles pun pada 1999 telah membuktikan teorema umum honeycomb conjecture: kisi-kisi (grid) segi enam merupakan cara terbaik untuk membagi sebuah bidang menjadi pecahan-pecahan sama luas dengan keliling paling sedikit.[24] Oleh karena itu, meskipun mereka berdua tidak membuktikannya secara matematis, nampaknya Al-Ghazālī dan Darwin tepat ketika berkeyakinan bahwa bentuk segi enam adalah bentuk yang paling baik untuk menyimpan sebanyak-banyaknya madu dengan menggunakan lilin sesedikit-sedikitnya.
Bukan tujuan tulisan ini untuk mengklaim Al-Ghazālī telah mendahului Darwin atau semacamnya. Melainkan, yang menarik adalah bagaimana keduanya kemudian menggunakan fakta tersebut untuk mendukung teori yang sama sekali berbeda. Al-Ghazālī menggunakannya sebagai bukti rahmat Allah pada seluruh makhluk (penjelasan teologis), sementara Darwin menggunakannya sebagai bukti teori seleksi alamnya (penjelasan naturalistik). Keduanya mengamati objek yang sama – aktivitas yang sekarang kita labeli sebagai sains – namun sampai pada kesimpulan yang berseberangan.
Barangkali inilah contoh konkret bahwa sains tidak selamanya netral. Ada paradigma yang digunakan, dan paradigma tersebut pada akhirnya bermuara pada pandangan alam (worldview) sang ilmuwan. Oleh karena itulah, pandangan alam dianggap sebagai kerangka kerja yang mendasari segala aktivitas ilmiah (general framework out of which follow scientific and technological activities).[25] Dalam hal ini, pandangan alam naturalistik dan tawhīd tentunya berbeda dalam menyikapi sebuah fenomena alam.
Dalam pandangan alam Islam, alam semesta – sebagaimana kitab suci Al-Qur’an – dideskripsikan sebagai “buku” yang berbicara tentang penciptanya.[26] Alam semesta disebut sebagai ayat kawniyyah yang didampingkan dengan Al-Qur’an sebagai ayat qawliyyah. Maka hakikat sains dalam pandangan alam Islam adalah mempelajari alam sebagai tanda (āyāt) keberadaan Sang Pencipta. Sebagaimana yang ditulis Prof. Al-Attas, “Now the word as it really is is a sign, a symbol; and to know it as it really is is to know what is stand for, what it symbolizes, what it means. To study the word as word, regarding as if it had an independent reality of its own, is to miss the real point of studying it….”[27]
Namun sebagaimana ayat qawliyyah ada yang muḥkamāt (jelas) dan ada yang mutasyābihāt (samar-samar), ayat kawniyyah pun terdiri dari ayat muḥkamāt dan mutasyābihāt. Sayangnya, karena alam semesta bersifat fisik, secara umum ia bersifat samar-samar dan sekilas terlihat seperti memiliki realitas yang independen.[28] Maka dari itu, penjelasan naturalistik ala Darwin[29] bisa dikatakan sebagai sains yang lahir dari alam semesta yang dipandang sebagai realitas independen. Akan tetapi, penjelasan Darwin meskipun didukung oleh fakta empiris tetap tidak sejalan dengan konsep sains dalam pandangan alam Islam, yaitu mengkaji alam semesta sebagai ayat Allah. Alih-alih memandang alam sebagai tanda keberadaan Allah, penjelasan naturalistik Darwin lebih sinkron dengan salah satu tabiat sekularisme, yaitu disenchantment of nature.[30] Alam diceraikan dari pesona ilahi, sehingga yang tersisa adalah penjelasan naturalistik yang tentunya tidak memandang alam semesta sebagai tanda kebesaran Allah.
Sebaliknya, penjelasan Al-Ghazālī sangat selaras dengan konsep alam sebagai ayat dalam pandangan alam Islam, meskipun barangkali bukti empirisnya tidak sebanyak Darwin (namun ini bisa dimaklumi karena Jawāhir Al-Qur’ān bukan kitab sains). Al-Ghazālī berangkat dari pengamatan empiris terhadap alam, namun fakta empiris yang beliau dapat ditempatkan dalam kerangka (framework) pandangan alam Islam. Alhasil, Al-Ghazālī mampu mengaitkan antara fakta keistimewaan bentuk segi enam sarang lebah madu dengan sifat Allah sebagai Maha Pengasih (Ar-Raḥmān) dan Maha Penyayang (Ar-Raḥīm).
Penutup
Pada tulisan ini, kita telah melihat bagaimana suatu fenomena alam dapat ditafsirkan ke dalam pandangan alam Islam maupun sekular, dan keduanya menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula. Al-Ghazālī, menggunakan kerangka pandangan alam Islam, mengaitkan bentuk segi enam sarang lebah madu dengan bukti rahmat Allah bagi seluruh makhluk ciptaan-Nya. Darwin, mengandalkan penjelasan naturalistik sebagai konsekuensi logis sekularisme, juga mengaitkan fakta yang sama dengan teori seleksi alamnya.
Maka sains tidak selamanya merupakan fakta kering (dry facts) tanpa muatan nilai apapun. Sains pun tidak sama dengan fakta, karena sains adalah interpretasi sang ilmuwan dari fakta yang diamati. Dan telah kita sama-sama ketahui dari bahasan ini, bagaimana pandangan alam seseorang dapat mempengaruhi kesimpulan yang diambil dari sebuah pengamatan fenomena alam.
Oleh karena itu, yang perlu dilakukan adalah evaluasi kritis bagaimana menempatkan sebuah fakta ke dalam kerangka pandangan alam Islam. Hal ini penting perlu dilakukan, karena sekarang pun filsafat modern telah menjadi penafsir dari sains modern.[31] Prof. Al-Attas menyadari situasi ini, maka sangat logis ketika beliau mengajukan bahwa interpretasi dan arah penyelidikan dari sains modern perlu dikritisi.[32] Inilah yang seharusnya menjadi perhatian umat Islam, yaitu mengembangkan sains dengan kerangka pandangan alam Islam.
Wallāhu a‘lam biṣ-ṣawāb.
***
Daftar Pustaka
Abū Ḥāmid Al-Ghazālī, The Jewels of the Qur’an: Al-Ghazali’s Theory (terj. Jawāhir Al-Qur’ān), Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1977.
Alparslan Açıkgenç, Scientific Thought and Its Burdens: An Essay in the History and Philosophy of Science, Istanbul: Fatih University Publications, 2000.
B.L. Karihaloo, K. Zhang, J. Wang, Honeybee Combs: How the Circular Cells Transform into Rounded Hexagons, Journal of the Royal Society Interface 10: 20130299, 2013.
Charles Darwin, On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life, London: John Murray, 1859.
Francesco Nazzi, The Hexagonal Shape of the Honeycomb Cells Depends on the Construction Behavior of Bees, Scientific Reports 6, 28341, 2016.
Marcus Porcius Cato & Marcus Terentius Varro, Cato and Varro: On Agriculture, Cambridge: Harvard University Press, 1934.
Muzaffar Iqbal, Darwin’s Shadow: Context and Reception in the Western World, Islam & Science, vol. 6, no. 2, 2008.
Robert J. Richards, Instinct and Intelligence in British Natural Theology: Some Contributions to Darwin’s Theory of the Evolution of Behavior, Journal of the History of Biology, vol. 14, no. 2, 1981, pp. 193-230.
Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Islām & Secularism, Kuala Lumpur: ISTAC, 1993 (cet. pertama 1978).
Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Prolegomena to the Metaphysics of Islām: An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islām, Kuala Lumpur: ISTAC, 1995.
Syed Muhammad Naquib Al-Attas, The Positive Aspects of Taṣawwuf: Preliminary Thoughts on an Islamic Philosophy of Science, Kuala Lumpur: ASASI, 1981.
Thomas Heath, A History of Greek Mathematics, Vol. II, Oxford: Clarendon Press, 1921.
T.C. Hales, The Honeycomb Conjecture, Discrete and Computational Geometry 25, 2001, hlm. 1-22.
William Kirby, On the Power, Wisdom and Goodness of God as Manifested in the Creation of Animals and in Their History, Habits, and Instincts, vol. 2, New York: Cambridge University Press, 2009.
https://www.darwinproject.ac.uk/commentary/life-sciences/evolution-honeycomb, diakses 4 November 2020 pukul 04:39 WIB.
Ucapan Terimakasih
Tulisan ini terinspirasi dari ceramah Dr. Muzaffar Iqbal berjudul Islam, Muslims, and the Challenge of Evolution yang dipresentasikan pada CILE 3rd Annual International Conference 2015 dengan tema “Islam and Modern Ethical Dilemmas”. Selain itu, tulisan beliau di jurnal Islam & Science berjudul Jewels, Honey, Blindness, and Sight (2007) juga sangat membantu penulis dalam merumuskan gagasan-gagasan pada tulisan ini. Oleh karena itu, penulis berterimakasih kepada Dr. Muzaffar Iqbal atas inspirasinya dalam membuat tulisan ini.
[1] Marcus Porcius Cato & Marcus Terentius Varro, Cato and Varro: On Agriculture, Cambridge: Harvard University Press, 1934, hlm. 501. Kalimat lengkapnya berbunyi: “Does not the chamber in the comb have six angles, the same number as the bee has feet? The geometricians prove that this hexagon inscribed in a circular figure encloses the greatest amount of space.”
[2] Thomas Heath, A History of Greek Mathematics, Vol. II, Oxford: Clarendon Press, 1921, hlm. 390. Kalimat lengkapnya berbunyi: “Bees, then, know just this fact which is of service to themselves, that the hexagon is greater than the square and the triangle and will hold more honey for the same expenditure of material used in constructing the different figures.”
[3] Abū Ḥāmid Al-Ghazālī, Jawāhir Al-Qur’ān, diterjemahkan oleh Muhammad Abul Quasem menjadi The Jewels of the Qur’an: Al-Ghazali’s Theory, Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1977.
[4] Ibid, hlm.67. Cetak tebal oleh penulis.
[5] Ibid, hlm. 68-69. Cetak tebal oleh penulis.
[6] Charles Darwin, On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life, London: John Murray, 1859.
[7] William Kirby, On the Power, Wisdom and Goodness of God as Manifested in the Creation of Animals and in Their History, Habits, and Instincts, vol. 2, New York: Cambridge University Press, 2009 (cet. pertama 1835), hlm. 337. Lihat juga https://www.darwinproject.ac.uk/commentary/life-sciences/evolution-honeycomb, diakses 4 November 2020 pukul 04:39 WIB.
[8] Robert J. Richards, Instinct and Intelligence in British Natural Theology: Some Contributions to Darwin’s Theory of the Evolution of Behavior, Journal of the History of Biology, vol. 14, no. 2, 1981, hlm. 211-212.
[9] Charles Darwin, On the Origin of Species…., hlm. 207. Cetak tebal oleh penulis.
[10] Ibid, hlm. 207-209, 211.
[11] Ibid, hlm. 209.
[12] Ibid, hlm. 216. Cetak tebal oleh penulis.
[13] https://www.darwinproject.ac.uk/commentary/life-sciences/evolution-honeycomb.
[14] Charles Darwin, On the Origin of Species…., hlm. 225-226.
[15] Ibid, hlm. 226-228.
[16] Ibid, hlm. 227-228.
[17] Ibid, hlm. 228. Sebuah laporan terbaru di Nature mengkonfirmasi hal ini. Pada laporan tersebut, penelitinya mengamati bahwa jika tidak ada sel lain yang berdekatan dengan sebuah sel, bentuk dinding-dinding ujung dari sel tersebut akan menyerupai lingkaran dan tidak bersudut. Akan tetapi, jika ada sel lain yang berdekatan, dinding pemisah antara keduanya akan berbentuk rata layaknya sisi segi enam. Akan tetapi, masih diperdebatkan apakah dinding segi enam itu dibuat dari awal oleh para lebah madu ataukah bermula dari sel lingkaran yang kemudian memanas hingga menjadi segi enam. Lebih lengkapnya, lihat Francesco Nazzi, The Hexagonal Shape of the Honeycomb Cells Depends on the Construction Behavior of Bees, Scientific Reports 6, 28341, 2016. Lihat juga B.L. Karihaloo, K. Zhang, J. Wang, Honeybee Combs: How the Circular Cells Transform into Rounded Hexagons, Journal of the Royal Society Interface 10: 20130299, 2013.
[18] Ibid, hlm. 228-229.
[19] Ibid, hlm. 231-234. Lihat juga Francesco Nazzi, The Hexagonal Shape…., hlm. 2-3.
[20] Ibid, hlm. 235.
[21] Ibid, hlm. 233.
[22] Ibid, hlm. 235. Cetak tebal oleh penulis.
[23] Secara geometris sebenarnya lingkaran memiliki rasio luas per keliling yang lebih besar dari segi enam. Akan tetapi, hanya segitiga sama sisi, persegi, dan segi enamlah yang mampu disusun secara bertumpuk tanpa menyisakan ruang kosong. Oleh karena itu, hanya ketiga bentuk tersebut yang dipertimbangkan dalam opsi bentuk sarang lebah madu.
[24] Lihat T.C. Hales, The Honeycomb Conjecture, Discrete and Computational Geometry 25, 2001, hlm. 1-22.
[25] Alparslan Açıkgenç, Scientific Thought and Its Burdens: An Essay in the History and Philosophy of Science, Istanbul: Fatih University Publications, 2000, hlm. 82-83.
[26] Syed Muhammad Naquib Al-Attas, The Positive Aspects of Taṣawwuf: Preliminary Thoughts on an Islamic Philosophy of Science, Kuala Lumpur: ASASI, 1981, hlm. 7.
[27] Ibid, hlm. 6. Cetak tebal oleh penulis.
[28] Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Prolegomena to the Metaphysics of Islām: An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islām, Kuala Lumpur: ISTAC, 1995, hlm. 136.
[29] Mengenai konteks intelektual Darwin serta pandangannya terhhadap kosmologi dan agama di saat ia menerbitkan bukunya, lihat Muzaffar Iqbal, Darwin’s Shadow: Context and Reception in the Western World, Islam & Science, vol. 6, no. 2, 2008, hlm. 99-122.
[30] Mengenai sekularisme dan disenchantment of nature, lihat Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Islām & Secularism, Kuala Lumpur: ISTAC, 1993 (cet. pertama 1978), hlm. 17-20.
[31] Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Prolegomena…., hlm. 113.
[32] Ibid.